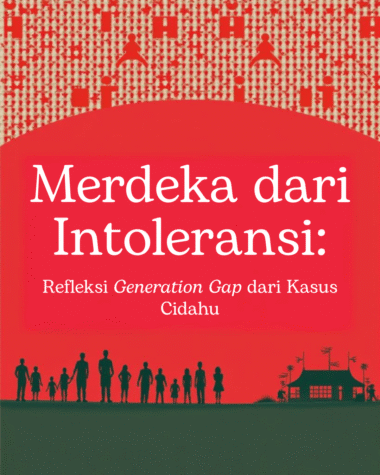
Oleh Pdt. Mike Makahenggang
Sudah menjadi luka lama jika di Indonesia sering terjadi aksi-aksi intoleransi yang dilakukan oleh kelompok/oknum tertentu kepada kelompok minoritas. Sayangnya, tidak banyak kasus yang kemudian diusut sampai tuntas. Hal demikian pun akhirnya menggiring opini di masyarakat bahwa ada keterlibatan dari pihak aparat maupun pemerintah setempat.
Tulisan ini berangkat dari peristiwa yang dialami sekelompok remaja-pemuda di Sukabumi yang sedang melaksanakan kegiatan retreat. Mereka mengalami tindakan kekerasan dari sekelompok orang yang merasa terusik dengan kegiatan tersebut, termasuk menyebut kegiatan retreat yang dilakukan bersifat ilegal, karena tidak memiliki izin dari pemerintah setempat.
Sebelum membahas lebih jauh, mari kita bersama pahami apa itu retreat? Kata “retret/ retreat/ritreat” dalam arti etimologisnya berarti penarikan diri. Di Katolik, retreat berarti penarikan diri dari hal-hal duniawi untuk menuju ke hal-hal yang adikodrati, meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi untuk menemukan hal-hal yang kekal, mengorbankan hal-hal yang bersifat manusiawi untuk memperoleh hal-hal yang Ilahi.
Pemaknaan ini diambil dengan mengingat seluruh sejarah manusia ini menjadi saksi atas fakta, bahwa setiap kali Allah ingin melibatkan manusia dalam karya-Nya sebagai alat pilihannya, manusia itu harus “menarik diri” dari dunia dan dari cara hidupnya yang lama. Untuk kemudian menemukan Allah dan menjadi peka kepada tanda-tanda yang ditunjukan Allah.
Kemudian dalam perkembangan zaman, retreat mengalami perkembangan pemaknaan serta tujuannya. Tidak lagi hanya sekadar menarik diri. Lebih dari itu, baik untuk individu maupun kelompok, menyediakan waktu dan kesempatan bagi refleksi diri, pemulihan, pengembangan diri, dan peningkatan kualitas hubungan, baik secara spiritual maupun profesional, dengan menjauhkan diri dari rutinitas dan kesibukan sehari-hari.
Bahkan bagi kelompok, melakukan retreat bertujuan meningkatkan kerjasama, melakukan evaluasi, dan menyusun perencanaan ke depan. Retreat meningkatkan pembentukan karakter, moral, motivasi, serta meningkatkan kembali semangat berkarya di dalam tim. Maka, tidak heran jika yang melaksanakan kegiatan retreat tidak selalu kelompok dari sebuah gereja, atau komunitas keagamaan tertentu. Namun, dapat juga dilakukan lembaga pendidikan, perusahaan atau komunitas-komunitas.
Jika kita berupaya mencari tahu, lalu bersama-sama memahami maksud dan tujuan dari kegiatan retreat, apakah mungkin insiden intoleransi seperti yang kita telah ketahui bersama dapat terjadi? Saya secara pribadi sangat optimis bahwa tidak akan mungkin terjadi.
Oleh karena itu, saya bisa asumsikan pihak/oknum, atau kelompok yang telah melakukan kekerasan ketika itu, adalah mereka yang tidak memahami kegiatan yang sedang berlangsung di lokasi kediaman keluarga Ibu Ina tersebut.
Jika demikian bagaimana dengan pihak aparat yang juga ada di lokasi kejadian, yang seakan-akan membiarkan tindakan yang dilakukan oleh oknum penyerangan itu? Apakah mereka tidak mencari tahu, sehingga tak paham juga? Atau kita boleh menyimpulkan, bahwa aparat di Indonesia hanya dilatih untuk menjadi prajurit yang patuh, bukan menjadi prajurit yang membela bahkan mengutamakan hak-hak kemanusiaan.
Selanjutnya, coba kita sama-sama amati, usia para penyerang itu kebanyakan berapa? Apakah masih anak muda, atau sudah orang dewasa, bahkan paruh baya? Sependek yang saya perhatikan dari video yang beredar, yang aktif melakukan pengrusakan adalah orang dewasa bahkan yang sudah cukup senior (usia 45-50an tahun).
Usia yang sudah memasuki jenjang sebagai orangtua, yang sejatinya telah punya sedikit pemahaman tentang apa itu retreat, atau justru mereka mengetahui, tetapi pola pikir mereka yakni sistem/pendekatan antar generasi cukup bisa membuat kesalahpahaman. Hal ini yang akan selanjutnya menjadi bahasan utama di tulisan ini.
Saya cerita sedikit. Tanggal 7 Juli 2025 lalu, saya berkesempatan mengikuti seminar di kalangan dosen-dosen STAK Marturia dengan topik Teologi – Teknologi dan perkembangan generasi. Dalam materinya, Dr. Leonard Chrysostomos Epafras (Dosen dan peneliti UGM), menjelaskan bahwa pada hakikatnya orang dewasa terbagi dalam dua generasi, yaitu generasi Boomers VS generasi Zoomers, dan perkembangan generasi tersebut sangat mempengaruhi banyak hal.
Untuk generasi Boomers disebut dengan istilah mencari jaringan terkuat wifi, yang artinya, generasi ini akan selalu terkoneksi dengan sesuatu yang memiliki power atau otoritas lebih dari dirinya. Mereka akan berusaha patuh dan hormat. Dengan demikian, generasi ini akan selalu menunjung tinggi setiap keputusan yang diberikan seseorang yang memiliki otoritas, seperti pimpinan di perusahaan, tokoh agama, seorang yang lebih senior dan memiliki jabatan di dalam sebuah kelompok.
Sedangkan generasi Zoomers istilahnya, mencari jaringan terdekat wifi. Generasi ini akan lebih hormat bahkan peduli kepada siapa yang dirasa lebih dekat dengannya. Mereka tidak dapat bertahan untuk patuh dengan pihak tertentu dalam waktu yang panjang, karena mereka dapat kagum dengan orang yang baru dikenal asalkan mereka intens ketemu, dan akan sangat mudah untuk segera memberikan penghormatan lebih. Mereka akan mudah move on dengan seseorang, atau pihak tempat kerjanya dan kemudian membangun relasi baru jika dirasa itu tidak menguntungkan untuknya. Bahkan, kepada pemimpin agama mereka dapat patuh, tapi di lain kesempatan akan dipandang sebagai teman yang perkataannya tidak selalu benar.
Sistem kepemimpinan dari kedua generasi ini juga berbeda. Generasi Boomers sistemnya adalah hierarki atau disimbolkan seperti pohon yang memiliki akar yang kuat ke bawah dengan batang pohon tunggal, dan dari situlah muncul buah dan daun. Dengan konsep kepemimpinan yang ‘top down’ maka segala hal yang dikatakan dari atas maka kewajiban yang di bawahnya adalah melakukan.
Namun, generasi Zoomers disimbolkan dengan tanaman jahe, yaitu sekalipun tunas sudah tertanam di tengah, tapi ia juga dapat menjalar kemana-mana. Konsep ini menunjukan pola perilaku mereka yang tidak selalu ‘fanatik kepada pemimpin’, tetapi menemukan apa yang menguntungkan dan menyenangkan diri sendiri. Generasi Zoomer selalu membuka jejaring dengan pihak luar sehingga akar mereka umumnya tidak fokus kepada hal atau sosok tertentu, tetapi menjalar berbagai arah.
Melalui penjelasan atas hasil riset dari Dr. Leonard di atas apakah kita bisa memberikan kesimpulan sederhana bahwa tindakan kekerasan dan penyerangan itu tidak terlepas dari pola perilaku generasi yang telah kita bahas. Tidak lagi pendekatannya adalah agama/keyakinan, kelompok minoritas VS mayoritas tetapi ini juga merambat kepada perkembangan psikologi, di mana adanya pengaruh perbedaan pola pikir generasi-generasi yang ada.
Mungkinkah oknum yang melakukan tindakan itu, karena merasa perkataan atasan adalah perintah yang harus dilakukan? Bila demikian, maka kasus intoleransi ini tidak hanya harus kita selesaikan pada sistem kelompok-kelompok radikal. Namun, seharusnya juga sebagai pekerjaan rumah kita semua, untuk menyiapkan generasi-generasi yang paham tentang Indonesia yang beragam ini, tidak melihat perbedaan sebagai ancaman, melainkan serupa kekayaan iman.
Saat akan menyelesaikan tulisan ini, saya mengikuti proses tindak lanjut oleh Kepolisian, tetutama ketika para istri mengajukan proses penangguhan karena berefek pada ekonomi. Saya jadi berpikir apakah para pelaku sempat berpikir sebelum keadaan ini terjadi? Bagaimana efeknya, bagaimana proses ganti rugi, siapa yang akan dirugikan, apakah melanggar hukum? Atau menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat.
Bila tidak, usah kita berbicara agama, melainkan menyadari betul bahwa inilah cerminan karakter masyarakat Indonesia. Selalu memosisikan sebagai korban, yang paling menderita, paling miskin, paling tersakiti, tetapi tidak memikirkan bagaimana bila melakukan tindakan tertentu, yang buruk kepada orang lain.
Melihat mereka para ibu dan bapak yang pada hakikatnya bertugas mendidik anak-anak, dapat dibayangkan bagaimana anak-anak yang dididik dengan karakter dan perilaku seperti halnya orang tuanya tersebut.
Situasi ini seharusnya menjadi tugas Negara dalam mendorong semua sistem dan lembaga di Indonesia untuk dapat membenahi diri. Di antaranya bagaimana lembaga pendidikan dapat merancang model pembelajaran yang tidak hanya fokus kepada teori, melainkan juga praktek dengan membuka ruang perjumpaan dengan beragam masyarakat.
Demikian juga dengan lembaga keagamaan sebaiknya memiliki pandangan yang sama. Bahwa agama adalah wadah umat untuk mengalami Tuhan dan berjumpa dengan ciptaan-Nya, bukan hanya untuk sibuk berdaya upaya mengajak seseorang agar masuk dan memperbesar jumlah umat dari agama tersebut saja.
Saya ingin kita sama-sama menyadari bahwa ranah keyakinan adalah privasi setiap manusia. Dan, pemimipin agama bukan sekadar bertugas mengantarkan umat menuju surga, tetapi menjadi teman seperjalanan yang bersama-sama berusaha untuk hikmat Tuhan. Seperti halnya Yesus ketika bersama para murid-murid, dalam Injil Yohanes 13:34 “Aku memberi perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi”.
Setiap agama bertugas memuliakan Tuhan dengan cara menghormati ciptaan-Nya, salah satunya menghargai sesama manusia. Oleh karena itu, mari kita sadari bersama bahwa konsep toleransi sebaiknya tak terbatas menjadi bahasan oleh atau antar tokoh agama maupun menjadi topik di kalangan pendidik, termasuk sekadar bahan diskusi di kelompok organisasi.
Kasus Cidahu mengajarkan kita bahwa konsep toleransi, hidup bersama, bekerjasama dalam masyarakat Indonesia yang beragam perlu dimulai dari keluarga. Karena apapun pergerakan yang dilakukan tokoh agama, lembaga pendidikan dan yang lainnya akan menjadi sangat sulit, bila tidak dimulai dari keluarga.















