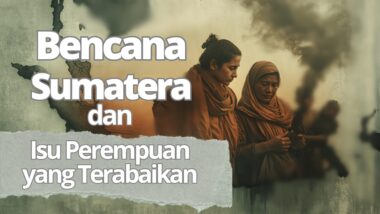Oleh Nuraini Chaniago
Tulisan ini saya awali dengan kasus-kasus yang terjadi terhadap kondisi umum perempuan di Indonesia. Menurut catatan Komnas Perempuan tahun 2024 terjadi peningkatan 14.17% kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBG), yaitu sebesar 330.097 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Di antaranya, 28.789 kasus merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga, di mana mayoritas korban dari kasus-kasus tersebut adalah perempuan.
Tak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan juga terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sumbar telah terjadi 33 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang Desember 2024.
Kepala DP3AP2KB Sumbar menyatakan bahwa kasus tersebut tersebar di beberapa wilayah di Sumatera Barat, di antaranya Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Solok Selatan, Sawahlunto dan Kota Padang. Dominasi dari kasus-kasus tersebut terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, dan fasilitas umum. Tempat-tempat yang kita anggap semestinya tempat aman untuk anak dan perempuan bertumbuh dalam banyak hal, tetapi realitas menunjukkan sebaliknya.
Saya pun bertanya-tanya, apa sesungguhnya yang terjadi pada masyarakat Minagkabau hari ini?
Minangkabau dikenal sebagai salah satu kelompok etnis di Indonesia dengan budaya, tradisi, serta sistem sosialnya yang unik. Sistem sosial yang dianut masyarakat Minangkabau adalah sistem matrilineal, yaitu sistem garis keturunan yang mengikuti garis ibu. Dengan demikian, secara normatif dan sesungguhnya kedudukan perempuan di Minangkabau begitu istimewa, baik dalam mengambil keputusan maupun dalam pembagian harta pusaka. Lalu, apakah hal tersebut sesuai dengan realitas hari ini? Dengan terjadinya banyak kasus kekerasan, benarkah bahwa hak dan akses perempuan sudah berjalan sebagaimana mestinya di tengah-tengah masyarakat Minang?
Beberapa waktu lalu saya berdiskusi dengan beberapa teman laki-laki perihal isu perempuan, keadilan gender, serta budaya patriarki yang masih terjadi di realitas masyarakat Minang. Dari banyaknya pro kontra dalam diskusi tersebut, satu hal yang menarik ialah, pernyataan bahwa Minangkabau itu tidak butuh feminis, terutama karena tidak ada budaya patriarki yang perlu dilawan. Perempuan di Minangkabau sudah memiliki hak yang begitu istimewa dengan matriarkinya.
Matriarki sendiri adalah sistem sosial dimana perempuan memiliki peran dominan dalam masyarakat, termasuk dalam pengambilan keputusan, hak waris, dan kepemimpinan. Dalam sistem tersebut kedudukan seorang ibu atau perempuan dewasa memiliki kekuasaan mutlak dalam kelompok keluarga, serta anak-anaknya dalam mengambil nama keluarga dari sisi ibunya.
Sementara, patriarki merupakah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam berbagai peran di masyarakat. Sebuah budaya yang menganggap bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan kedudukan perempuan, dan perempuan seringkali dianggap sebagai pihak yang subordinat atau bisa dibilang rentan.
Secara teoritis dan normatif, memang kedudukan perempuan di Minangkabau itu seharusnya sangat istimewa dengan sistem matrilinealnya. Ketika terjadinya perceraian dalam keluarga perempuan Minang, misalnya, maka yang berhak memperoleh seluruh harta suami istri adalah perempuan, sedangkan laki-laki hanya ke luar dari rumah mantan istrinya dengan membawa diri saja.
Namun, realitas hak dan akses perempuan Minang tidaklah sesederhana itu. Salah satu yang perlu diingat, bahwa sistem matriarki di Minangkabau bukan semata-mata untuk melawan ataupun mendominasi laki-laki melainkan untuk menentang budaya yang tidak adil terhadap perempuan. Hal ini perlu dikedepankan dalam membedakan apa itu matriarki dan patriarki, karena yang dilawan bukanlah Minangnya, melainkan pihak-pihak yang melanggengkan budaya patriarki tersebut.
Fakta yang berbeda juga ditemukan, ketika beberapa perempuan Minang akhir-akhir ini mendapatkan perlakuan yang diskriminatif hanya karena ia perempuan. Contoh kasusnya dalam rumah tangga, masih banyak perempuan Minang yang dibebankan dengan stigma dan beban ganda hanya karena ia perempuan, baik di ranah domestik maupun publik. Banyak perempuan Minang hari ini belum mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, karena harus mendapatkan persetujuan utama dari pihak keluarga laki-laki, baik itu dari suadara laki-lakinya, suaminya, maupun niniek mamaknya, agar tidak dilabeli sebagai perempuan yang tidak beradat atau tidak mencirikan perempuan Minang itu sendiri.
Tak hanya itu, ketika ditemukan suami membantu istri mengerjakan pekerjaan domestik, seperti mengurus anak dan mengerjakan pekerjaan rumah, maka stigma negatif keluarga dan masyarakat terhadap perempuan akan tumbuh subur, seperti dianggap sebagai perempuan yang tidak menghormati suami, atau suami takut istri, atau perempuan yang tidak mengerti kodratnya sebagai perempuan. Padahal relasi yang sehat antar gender adalah relasi yang penuh kesalingan antara laki-laki dan perempuan di dalam ranah domestik maupun publik.
Beberapa teman saya pernah bercerita, sebagai perempuan yang sudah menikah, dia tidak mendapatkan izin suaminya untuk melanjutkan sekolah dan berkegiatan di luar rumah. Meskipun dari awal pernikahan mereka sudah punya kesepakatan untuk saling memberikan ruang bertumbuh antara suami istri sesuai passionnya masing-masingnya, namun realitasnya tidak begitu. Ia dipaksa tunduk karena takut dilabeli keluarga sebagai istri yang durhaka dan tidak baik.
Di tempat lain misalnya, ketika ada teman-teman perempuan Minang yang mendapatkan perlakuan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, baik di rumah, sekolah, kampus, tempat kerja, organisasi dan lain sebagainya. Suara mereka dibungkam oleh pihak-pihak yang memiliki relasi kuasa karena dianggap aib, ataupun kesaksiannya dianggap sebagai sesuatu yang tidak serius. Hal semacam ini masih tumbuh subur di masyarakat Minangkabau, dan lagi-lagi yang rentan menjadi korban utama adalah perempuan.
Mengakhiri tulisan ini, mari kita sama-sama membuka pikiran dalam melihat kasus-kasus kemanusiaan hari ini, termasuk permasalahan-permasalahan perempuan secara realitas, bukan hanya teoritis. Mari kita sama-sama belajar untuk terus melihat laki-laki dan perempuan sebagai manusia utuh yang perlu diberlakukan layaknya manusia bukan karena jenis kelaminnya. Yang kita lawan itu bukan Minangnya atau agamanya, melainkan aktor-aktor yang melanggengkan sistem patriarki tersebut; yang lebih banyak mendatangkan kemudaratannya dibandingkan kemaslahatannya.